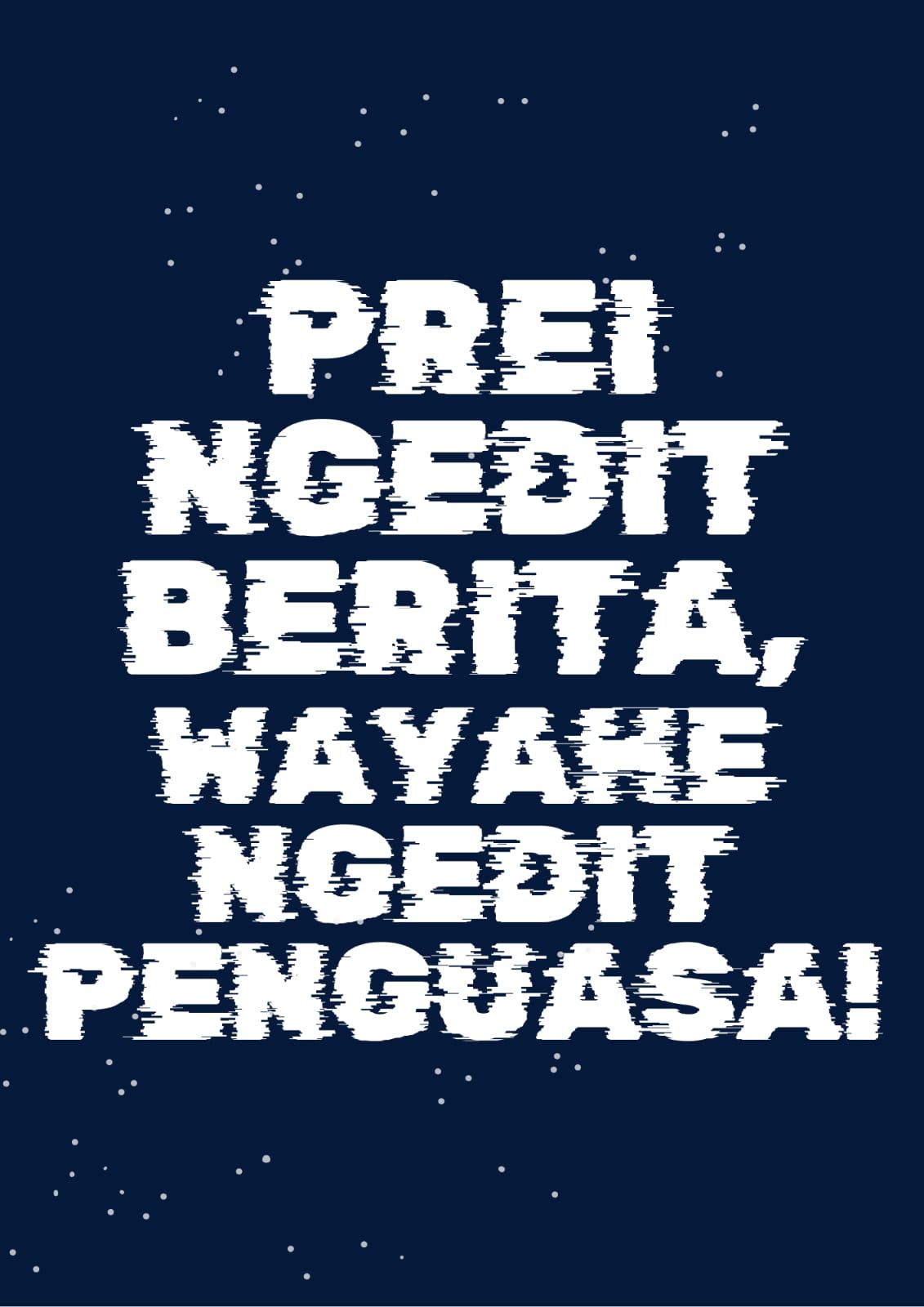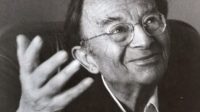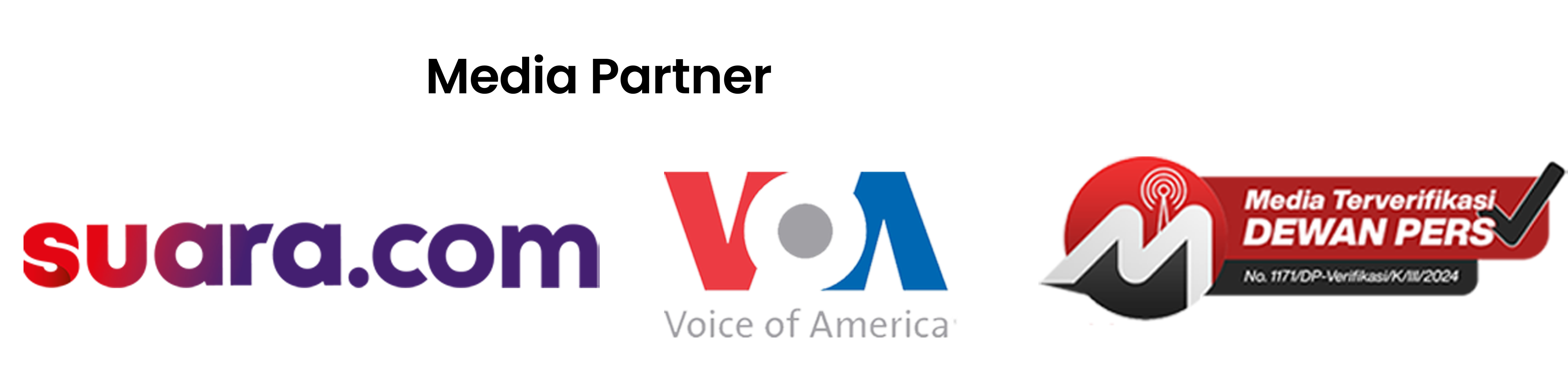Oleh : Imam Mubarok, Pemred Metaranews.co
Metaranews.co – Pada peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, di tengah hiruk-pikuk orasi dan spanduk warna-warni, tampak sekumpulan jurnalis bergabung dalam barisan massa buruh.
Bagi mereka, 1 Mei bukan sekadar agenda liputan, melainkan cermin nasib mereka sendiri sebagai buruh media.
Bayang-bayang senjakala industri media menaungi langkah para pewarta itu – sebuah senja panjang yang ditandai pemutusan hubungan kerja massal, model bisnis rapuh yang kian tergantung pada iklan dan platform digital, hingga tuntutan kerja yang menggerus waktu dan kesejahteraan.
Di pundak merekalah predikat pilar keempat demokrasi disematkan, namun pilar itu kini goyah.
Melalui esai reflektif ini, mari merenungi kerasnya realitas yang dihadapi buruh jurnalis Indonesia, dan menggali urgensi solidaritas lintas profesi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja media.
PHK Massal di Senjakala Industri Media
Industri media di Indonesia tengah mengalami masa sulit bak senjakala yang suram. Satu per satu perusahaan pers melakukan efisiensi dengan PHK massal terhadap jurnalisnya.
Sejak pandemi Covid-19 melanda, ribuan pekerja media di seluruh Indonesia terkena gelombang pemutusan hubungan kerja.
Ironisnya, perusahaan media yang sebelumnya lantang mengkritik Omnibus Law (UU Cipta Kerja), karena dianggap merugikan kaum buruh, justru tak segan menggunakan celah hukum dalam UU tersebut untuk melancarkan PHK dengan biaya pesangon minimal.
Akibatnya, banyak jurnalis yang terpaksa hengkang dengan tangan hampa atau kompensasi jauh di bawah standar Undang-undang Ketenagakerjaan.
Fenomena ini bukan isapan jempol. Hasil riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2023 menunjukkan betapa rentannya kondisi kerja jurnalis: hampir 50 persen jurnalis menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Belasan persen lainnya bahkan mengaku upah mereka tidak menentu, bergantung pada komisi iklan atau honor lepas yang bisa berhenti kapan saja.
Ketika model bisnis media rapuh dan pendapatan iklan kian tersedot ke platform digital raksasa, perusahaan pers kerap menjadikan jurnalis korban pertama penghematan.
Tak ayal, ruang redaksi yang dulunya hiruk-pikuk kini banyak yang meredup; kursi-kursi kosong mengingatkan rekan yang “dirumahkan” dalam gelombang efisiensi.
Seorang jurnalis senior mengenang pahit, “Dulu tiap pagi ruang rapat penuh. Sekarang yang tersisa cuma separuh – sisanya terkena PHK atau mengundurkan diri sebelum ‘kapal media’ ini karam,” ucapannya menggambarkan ketidakpastian yang menghantui banyak pekerja media saat ini.
Model bisnis media yang rapuh juga memperparah senjakala ini. Selama bertahun-tahun, sebagian besar media mengandalkan iklan untuk bertahan hidup.
Namun, di era digital, kue iklan semakin mengecil untuk media berita, karena sebagian besar belanja iklan lari ke platform media sosial.
Media cetak konvensional telah lama merasakan penurunan oplah, sementara media siber harus berkejaran dengan click-rate dan algoritma platform yang berubah-ubah.
Tanpa inovasi model pendapatan lain (seperti langganan atau donasi), banyak perusahaan pers bagaikan berjalan di atas es tipis.
Sekali pendapatan anjlok, pilihan mereka sering ekstrem: pemotongan gaji, merumahkan karyawan, atau PHK massal. Inilah realitas keras industri media Indonesia yang tengah senja – dan para jurnalislah yang menanggung beban terberatnya.
Upah Rendah, Side Job, dan Jam Kerja yang Mencekik
Salah satu poster aksi May Day 2025 bertuliskan “Upah Jurnalis Tak Menentu, Bikin Gagal Jadi Menantu”, sindiran satiris bahwa penghasilan yang tidak pasti membuat jurnalis kesulitan membangun masa depan pribadi.
Poster tersebut menggambarkan bagaimana gaji kecil dan status kerja tak jelas menghantui kehidupan kaum jurnalis muda.
Bagi banyak jurnalis, gaji bulanan dari kantor media tidak lagi dapat diandalkan sebagai sandaran hidup. Separuh dari mereka bahkan dibayar di bawah standar minimum, dan sebagian hanya dibayar per berita yang tayang.
Artinya, ketika tidak ada berita yang ditulis atau ketika target klik tak tercapai, pundi-pundi mereka pun kosong. Ketidakpastian upah ini memaksa para jurnalis memutar otak untuk menyambung hidup.
Tak sedikit yang harus merangkap pekerjaan sampingan di luar jam liputan – menjadi pengemudi ojek online, berjualan daring, hingga freelance di bidang lain – demi memperoleh penghasilan tambahan.
“Gaji sebagai wartawan itu ibarat mimpi minum es lemon tea, tapi realitanya cuma sanggup beli teh paket hemat,” canda seorang reporter muda, mengacu pada seloroh populer “mimpinya ice lemon tea, jurnalis belinya teh cekik” yang beredar di kalangan mereka.
Di balik humor getir itu tersimpan fakta: tanpa side job, mungkin seorang jurnalis tak bisa memenuhi kebutuhan dasar apalagi menabung untuk masa depan.
Lebih parah lagi, status hubungan kerja banyak jurnalis pun rentan dan mengecoh. Menurut riset AJI, lebih dari 52 persen jurnalis berstatus kontrak waktu tertentu, dan sekitar 11 persen tampak berstatus karyawan tetap .
Namun, bahkan di antara yang “tetap” tersebut, banyak yang tidak digaji bulanan, melainkan dibayar berdasarkan jumlah artikel yang diterbitkan .
Dengan sistem honor per piece semacam itu, status “tetap” nyaris hanya nama – hak-hak mereka tak ubahnya pekerja kontrak tanpa kepastian. Situasi ini membuat jurnalis sulit merencanakan keuangan jangka panjang.
Bagaimana mungkin mereka mengambil kredit rumah atau merencanakan pernikahan bila penghasilan bulan depan saja tak jelas?
Tak heran bila poster “bikin gagal jadi menantu” tadi lahir dari realita pahit: pekerjaan sebagai jurnalis tak menjamin kestabilan ekonomi, bahkan untuk memenuhi ekspektasi sosial seperti membina keluarga.
Dengan nada humor gelap, sebuah poster memperlihatkan sosok berhelm kardus bertuliskan “Jurnalis Kerja Overtime, Jadi Tak Punya Me Time” Poster ini menyuarakan kelelahan kolektif para jurnalis yang kerap dipaksa bekerja di luar batas jam kerja normal, tanpa kesempatan beristirahat sejenak.
Selain bergaji rendah, jam kerja jurnalis sering kali melampaui batas wajar. Tuntutan lembur dan siap siaga 24 jam telah menjadi kelaziman di dunia media, apalagi di era internet ketika berita harus terus-menerus diperbarui.
Banyak jurnalis bercanda pahit bahwa telepon genggam mereka tak pernah benar-benar “offline” – selalu ada pesan editornya yang masuk tengah malam, selalu ada tugas mendadak di akhir pekan.
Bekerja di hari libur, pulang lewat tengah malam, atau begadang menuntaskan laporan mendalam sudah dianggap bagian dari risiko profesi.
Celakanya, kompensasi atas lembur ini sering nihil. Beberapa perusahaan pers tidak membayar overtime dengan dalih profesi jurnalis adalah pekerjaan kreatif atau posisi “bergaji bulanan” (meski jumlah bulanan itu minim).
Alhasil, kelelahan kronis menggerogoti para pewarta. Waktu untuk diri sendiri dan keluarga (istilah populernya “me time”) menjadi kemewahan yang sulit terjangkau. “Sudah jam 10 malam, berita belum kelar semua”.
“Mau istirahat rasanya berdosa,” kelakar seorang editor yang mengaku sudah sebulan lebih tak sempat makan malam bersama keluarganya.
Tuntutan produktivitas di newsroom digital – mengejar klik, impresi, dan tenggat – membuat jurnalis terperangkap dalam siklus kerja yang seolah tiada henti.
Kondisi kerja semacam ini jelas tidak ideal. Dalam jangka panjang, jurnalis dengan kesehatan fisik dan mental yang terforsir akan kesulitan menghasilkan karya bermutu.
Mereka rentan melakukan kesalahan, tidak punya waktu mendalami liputan, dan bisa kehilangan semangat idealisme.
Apa guna deadline terpenuhi jika jurnalisnya sendiri “habis” secara kemanusiaan? Pertanyaan reflektif ini mengemuka di benak banyak pekerja media hari ini.
Di tengah tekanan ekonomi yang membuat mereka harus kerja ekstra keras (bahkan di luar profesi), jurnalis mencoba tetap berpegang pada idealisme bahwa pekerjaan mereka penting bagi publik. Namun, idealisme saja tidak cukup mengisi perut atau membayar kontrakan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan makin banyak jurnalis berkompeten yang undur diri dari profesi, mencari nafkah di bidang lain yang lebih menjanjikan stabilitas.
Dan ketika para penjaga informasi publik berguguran, demokrasi kita semua yang akan merasakan akibatnya.
Pilar Demokrasi yang Kian Rapuh
Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi – setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif – karena perannya mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Namun, pilar ini akan tegak bila para jurnalis yang menopangnya berdiri kokoh. Faktanya kini, pilar itu mulai rapuh.
Eksploitasi terhadap buruh media bukan saja isu ketenagakerjaan semata, tapi ancaman serius bagi kualitas demokrasi.
AJI dalam seruan Hari Buruhnya menegaskan bahwa normalisasi praktik-praktik buruk di industri media akan merusak demokrasi, karena jurnalis yang dieksploitasi tidak dapat bekerja profesional dan menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.
Bagaimana pers bisa optimal menjalankan fungsi kontrol sosial jika para wartawannya sendiri harus pontang-panting memperjuangkan hak dasar mereka?
Selain masalah ekonomi, jurnalis juga menghadapi tekanan berupa kekerasan dan intimidasi dalam menjalankan tugas.
Tiap tahun, puluhan kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di Indonesia – mulai dari intimidasi verbal, perusakan alat kerja, pemukulan saat meliput aksi, hingga ancaman hukum dengan pasal karet.
Tahun 2023 lalu, AJI mencatat 89 kasus serangan terhadap jurnalis dan media, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Akan tetapi, dari puluhan kasus tersebut, hanya segelintir yang berujung pada penegakan hukum. Bahkan dilaporkan hanya dua kasus yang pelakunya berhasil dihukum di pengadilan , mencerminkan betapa mengakarnya budaya impunitas terhadap pelaku kekerasan pada pers.
Tahun 2024 situasinya tak jauh membaik – terdapat 73 kasus kekerasan yang terdokumentasi . Artinya hampir saban minggu ada saja jurnalis yang menjadi korban.
Situasi ini kian buruk bagi jurnalis perempuan. Mereka menghadapi kerentanan ganda: sebagai jurnalis dan sebagai perempuan. Kekerasan berbasis gender acap mengintai jurnalis perempuan, baik kekerasan fisik di lapangan maupun pelecehan seksual, hingga perundungan daring.
Tak sedikit wartawati yang mendapat perlakuan merendahkan saat bertugas, dianggap “lebih lemah” oleh aparat keamanan atau massa kasar.
Dalam ruang redaksi pun, perempuan sering dihadapkan pada bias dan kesenjangan. Hak-hak khusus perempuan kerap diabaikan; hanya sekitar 11 persen jurnalis perempuan yang mengaku mendapat hak cuti haid hari pertama dan kedua dengan upah penuh.
Saat hamil atau melahirkan, banyak dari mereka yang tidak diberi cuti memadai – bahkan ada perusahaan media yang meminta jurnalis perempuan untuk tidak bekerja saat melahirkan tanpa memberikan upah.
Kondisi ini memaksa wartawati memilih antara karier dan keluarga, sebuah dilema yang mestinya tak perlu terjadi bila perusahaan memenuhi kewajiban dasar.
Di tengah situasi tersebut, seruan “Stop Kekerasan Pada Jurnalis Perempuan” terdengar lantang dalam aksi Hari Buruh tahun ini.
Poster berwarna oranye terang dengan tulisan tebal itu diangkat tinggi-tinggi, mewakili harapan agar tidak ada lagi kasus Liani maupun Nurhadi berikutnya – jurnalis-jurnalis yang mengalami kekerasan dan pelecehan karena menjalankan profesinya.
Para jurnalis perempuan dalam barisan itu bukan sekadar memperjuangkan diri sendiri, melainkan juga martabat profesi secara keseluruhan.
Sebab mereka sadar, keselamatan jurnalis adalah syarat mutlak tegaknya kebebasan pers. Jika jurnalis terus diintimidasi, maka publik akan kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan berimbang. Dan ketika suara pers bungkam oleh ancaman, yang diuntungkan hanyalah para tiran dan koruptor.
Dengan berbagai tekanan dari dalam (eksploitasi ekonomi) dan luar (kekerasan dan ancaman), wajar bila pers sebagai pilar demokrasi kini rawan retak.
Kita patut merenung: di negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, apakah nasib para penjaga informasi publik sudah diperhatikan sewajarnya?
Janji reformasi dan kemerdekaan pers rupanya belum menjamin kesejahteraan mereka yang bekerja di balik berita.
Kebebasan pers bukan hanya soal tidak adanya sensor, tapi juga kebebasan dari rasa takut – takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, takut diserang saat meliput, takut dipecat saat bersuara.
Selama jurnalis masih dihantui ketakutan-ketakutan itu, demokrasi kita sesungguhnya sedang sakit.
“May Day! May Day!” – Solidaritas dan Perlawanan di Hari Buruh
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyerukan para jurnalis: “Libur Dulu Ngetik Berita, Waktunya Turun ke Jalan!” pada peringatan Hari Buruh 2025.
Ajakan ini menggugah jurnalis untuk sejenak meninggalkan rutinitas newsroom dan bergabung menyuarakan hak-hak mereka di jalanan, berdiri bahu-membahu dengan gerakan buruh lainnya.
Di tengah rapuhnya kondisi buruh media, harapan justru muncul dari solidaritas. Pada Hari Buruh tahun ini, Aliansi Jurnalis Independen dan komunitas pekerja media di berbagai kota turun ke jalan bersama aliansi buruh lintas sektor.
Pemandangan yang tak biasa terlihat: jurnalis yang biasanya meliput demonstrasi, kini ikut berorasi. Sembari tetap membawa ID Press, mereka mengangkat poster-poster bernada kritis, mengundang senyum getir sekaligus tepuk tangan simpati dari massa buruh lainnya.
“Prei ngedit berita, wayahe ngedit penguasa! May Day! May Day!” seru salah satu poster berbahasa Jawa yang artinya kurang lebih “berhenti sejenak mengedit berita, ini waktunya mengoreksi para penguasa”.
Pesan itu menyentil bahwa di Hari Buruh, jurnalis pun menyuarakan kritik tajam kepada struktur kekuasaan dan industri yang selama ini abai pada kesejahteraan mereka.
Tuntutan yang dibawa AJI dan para jurnalis pada May Day 2025 sejalan dengan isu-isu krusial yang telah diuraikan: penghentian PHK semena-mena, upah layak, jaminan jam kerja yang manusiawi, perlindungan bagi jurnalis perempuan, dan stop kekerasan terhadap jurnalis.
Dalam siaran persnya, AJI menyerukan dibentuknya serikat pekerja di setiap perusahaan media maupun lintas media sebagai upaya kolektif melawan eksploitasi .
Serikat pekerja diyakini bisa memperkuat posisi tawar jurnalis terhadap manajemen media, sehingga keputusan sepihak yang merugikan karyawan bisa dilawan bersama.
Imbauan ini menggarisbawahi bahwa perjuangan jurnalis tak bisa sendiri-sendiri; harus ada payung kolektif yang melindungi, entah itu serikat di internal media ataupun federasi lintas media.
Lebih luas lagi, AJI menggalang solidaritas lintas profesi. Sebab persoalan yang dihadapi jurnalis sebenarnya senada dengan problem pekerja sektor lain di era ekonomi neo-liberal ini: hubungan kerja kontrak yang genting, upah murah, jam kerja panjang, dan minim perlindungan.
Jurnalis, buruh pabrik, guru honorer, tenaga kesehatan kontrak – semua berada dalam pusaran ketidakpastian hidup akibat kebijakan ekonomi yang mendewakan efisiensi ketimbang kesejahteraan pekerja.
Kesadaran inilah yang mendorong seruan agar ada solidaritas di antara semua elemen pekerja. Nasib buruh media adalah nasib buruh seluruhnya. Jika satu elemen dibiarkan lemah, perjuangan buruh secara keseluruhan turut melemah.
Seruan solidaritas ini juga tampak dalam dukungan berbagai komunitas kepada perjuangan jurnalis. Para aktivis buruh, LSM, hingga komunitas pers mahasiswa ikut menyuarakan isu pekerja media.
Mereka menyadari bahwa membela jurnalis bukan semata demi kesejahteraan segelintir profesional berpendidikan, tetapi demi hak publik atas informasi.
Kalimat sederhana itu mengena: memperjuangkan hak-hak buruh jurnalis sejatinya bagian dari memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar.
Demokrasi yang sehat butuh pers yang kuat; dan pers yang kuat lahir dari jurnalis yang sejahtera dan bebas dari tekanan.
Dalam aksi May Day 2025 ini, poster-poster kreatif menjadi media curhat sekaligus protes.
Selain slogan tentang upah dan jam kerja, ada pula “Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis” yang ditulis dengan latar merah menyala, mengingatkan publik bahwa wartawan bukan musuh yang boleh dihakimi di lapangan.
Poster itu dipajang berdampingan dengan poster “Stop Kekerasan Pada Jurnalis Perempuan”, menegaskan perhatian khusus pada perlindungan jurnalis wanita dari pelecehan.
Visual dan kata-kata tajam ini mengajak siapa pun yang melihat untuk merenung: ada problem serius dalam industri media kita.
Dan May Day menjadi panggung bagi jurnalis untuk menyuarakannya, bukan dengan tulisan berita seperti biasa, tapi dengan teriakan yel-yel dan pesan di karton.
Hari itu, pemandangan jurnalis turun ke jalan ibarat melihat cermin terbalik. Biasanya merekalah yang meliput derita kaum buruh; kini mereka menceritakan derita sendiri.
Langkah kaki para kuli tinta bersepatu kets di aspal menyatu dengan langkah kaki buruh pabrik, buruh tani, guru, dan pekerja sektor lain.
Di sinilah esensi solidaritas lintas profesi benar-benar terasa. Tidak ada kasta dalam perjuangan pekerja: keyboard, cangkul, maupun mesin pabrik sama-sama alat produksi yang dipegang orang kecil mencari nafkah.
Perjuangan buruh media bertautan erat dengan perjuangan buruh lain melawan ketidakadilan struktural.
Refleksi: Saatnya Menjaga Para Penjaga Kabar
Kondisi buruh jurnalis di Indonesia pada Hari Buruh 2025 ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga: para penyampai kabar membutuhkan kabar baik untuk diri mereka sendiri.
Mereka telah terlalu lama dianggap “panggilan hati” belaka, seolah-olah tidak butuh penghargaan material.
Padahal, idealisme pers akan sulit bertahan jika para jurnalis terus-menerus dicekik oleh rendahnya upah, ancaman PHK, jam kerja berlebih, dan maraknya kekerasan.
Kemunafikan terbesar adalah menyanjung pers sebagai pilar demokrasi, namun mengabaikan kesejahteraan dan keamanan mereka yang bekerja di baliknya.
Sudah waktunya semua pemangku kepentingan mengambil langkah. Perusahaan media harus berbenah, menghentikan eksploitasi dan memenuhi hak-hak normatif jurnalis sebagai pekerja.
Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers mengamanatkan kesejahteraan bagi wartawan dan karyawan media, dan perusahaan yang masih mengabaikannya berarti tidak memenuhi standar pers yang profesional.
Pemilik media perlu sadar bahwa investasi pada kesejahteraan jurnalis adalah investasi pada kualitas produk jurnalistik itu sendiri.
Media yang wartawannya terpaksa mencari nafkah tambahan atau khawatir di-PHK tentu sulit menghasilkan berita mendalam yang berintegritas.
Dari sisi pemerintah dan regulator, kebijakan yang melindungi pekerja media mendesak diperjuangkan.
Revisi regulasi tenaga kerja yang lebih adil, termasuk meninjau ulang pasal-pasal di UU Cipta Kerja yang melemahkan perlindungan pekerja, akan sangat berpengaruh bagi buruh media.
Pemerintah juga perlu mendorong perusahaan media mematuhi aturan ketenagakerjaan – misalnya memastikan jurnalis kontrak tidak terus menerus diperpanjang tanpa diangkat tetap, atau memastikan ada jaminan sosial dan kesehatan bagi mereka.
Selain itu, aparat penegak hukum harus serius menindak setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Impunitas harus diakhiri, karena pembiaran hanya akan melahirkan kekerasan baru. Negara berkewajiban menjamin pekerja media dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut.
Dan yang tak kalah penting, dari sisi jurnalis sendiri, keberanian berserikat dan bersuara kolektif harus ditingkatkan. Pengalaman menunjukkan bahwa hanya sedikit serikat pekerja media yang aktif saat ini.
Padahal, tanpa serikat yang kuat, jurnalis cenderung tersisih sendiri-sendiri ketika masalah terjadi. AJI dan komunitas pekerja media perlu terus memfasilitasi pembentukan serikat di berbagai perusahaan pers, serta jaringan lintas media.
Solidaritas internal profesi ini bisa menjadi benteng awal melawan kebijakan manajemen yang sewenang-wenang.
Kita telah melihat contoh berani seperti para jurnalis di CNN Indonesia yang mencoba membentuk serikat pekerja demi menolak pemotongan gaji – meski mereka akhirnya menghadapi PHK, perjuangan mereka mendapat sorotan luas dan membuka mata banyak jurnalis lain akan pentingnya persatuan. Ini menunjukkan perubahan hanya bisa terjadi jika ada nyali kolektif.
Akhirnya, refleksi ini kembali kepada kita, masyarakat luas. Publik perlu menyadari bahwa kesejahteraan jurnalis bukanlah isu elitis nan jauh, melainkan sesuatu yang akan berdampak langsung pada kualitas informasi yang kita konsumsi setiap hari.
Ketika kita menuntut berita yang akurat, investigasi mendalam, atau liputan yang berpihak pada rakyat kecil, ingatlah bahwa itu semua dikerjakan oleh manusia biasa bernama jurnalis.
Jika hidup mereka tidak sejahtera atau bebas, maka bagaimana mereka bisa maksimal membela kepentingan publik? Solidaritas lintas profesi berarti dukungan masyarakat sipil, komunitas pembaca, hingga gerakan sosial lainnya bagi perjuangan jurnalis.
Misalnya, saat ada kampanye melawan kekerasan jurnalis atau penggalangan dana solidaritas untuk jurnalis korban PHK, partisipasilah. Anggaplah itu investasi kecil untuk masa depan demokrasi kita.
Senja di industri media Indonesia mungkin tengah berlangsung, tetapi belum terlambat untuk mencegah malam gulita. Masih ada secercah cahaya – yakni kesadaran dan solidaritas.
Kisah para jurnalis yang turun ke jalan di Hari Buruh 2025 ini menyalakan harapan bahwa perubahan bisa diperjuangkan bersama. Bahwa nasib buruh media bukan hanya urusan segelintir orang, melainkan perjuangan kita semua yang peduli pada tegaknya kebenaran dan keadilan.
Saatnya menjaga para penjaga kabar. Memberi mereka perlindungan, penghidupan layak, dan rasa hormat yang sepantasnya.
Sebab ketika jurnalis bisa hidup dan bekerja dengan bermartabat, mereka akan leluasa menggenggam obor kebenaran untuk menerangi masyarakat. Dan dengan demikian, pilar keempat demokrasi akan kembali tegak berdiri, kokoh menopang rumah besar Indonesia yang adil dan bebas.